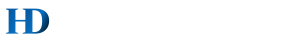Depok (13/11/2025) – Tuntutan publik terhadap Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukan lagi sekadar wacana, melainkan jeritan mendesak. Masyarakat mendambakan institusi penegak hukum yang mengabdi sepenuhnya kepada rakyat dan negara, bukan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Ironisnya, di balik slogan normatif “Polri untuk rakyat”, terhampar jurang lebar antara idealisme dan kenyataan pahit di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, bayang-bayang ketidakpercayaan publik kian pekat. Serangkaian insiden—mulai dari kekerasan terhadap warga sipil, perilaku amoral oknum, penembakan internal, hingga kasus mencurigakan seperti kematian Brigadir Nurhadi dan tragedi Affan Kurniawan—secara kolektif telah mencoreng wajah institusi.
Insiden-insiden ini bukan kecelakaan tunggal; mereka adalah cerminan bahwa reformasi yang selama ini digembar-gemborkan masih mandek di level administratif, gagal menyentuh akar struktural dan kultural kepolisian. Padahal, integritas dan profesionalisme Polri hanya bisa dicapai melalui transformasi total yang mencakup sistem pengawasan, rekrutmen, dan akuntabilitas yang transparan dan terukur.
Anggaran Fantastis, Akuntabilitas Nihil
Paradoks terbesar muncul dari sisi anggaran. Di tengah sorotan tajam dan penurunan kepercayaan publik, anggaran Polri justru terus melonjak dalam lima tahun terakhir. Puncaknya, pengajuan tambahan Rp 63,7 triliun untuk RAPBN 2026, menjadikan total anggaran mencapai Rp 173,3 triliun (Katadata, 15/8/2025).
Yang lebih ironis, sebagian besar pos anggaran ini dialokasikan untuk pengadaan alat pengamanan massa. Alih-alih investasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas, yang meningkat justru peralatan represif.
Dalam kacamata teknokratik, pertanyaan krusialnya bukan berapa uang negara digelontorkan, tetapi untuk apa dan apa hasilnya? Apakah kenaikan anggaran ini berkorelasi dengan:
- Peningkatan kualitas layanan publik?
- Penurunan angka pelanggaran etik?
- Membaiknya akuntabilitas kelembagaan?
Jika tidak, maka lonjakan anggaran ini hanya melanggengkan inefisiensi. Persoalan mendasar terletak pada sistem yang koruptif dan feodal. Mengutip W. Edwards Deming, “Bad system beats good people every time.” Selama sistem internal Polri tidak direformasi secara radikal, setiap pemimpin baru akan terjerumus ke dalam pola lama: korupsi, feodalisme, dan tindakan represif. Solusi sejati bukan sekadar ganti Kapolri, melainkan Pertobatan Institusional.
Komisi Reformasi: Kosmetik atau Transformasi?
Pelantikan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, awalnya diharapkan menjadi motor perubahan. Namun, struktur komisi ini justru menimbulkan pesimisme.
Kelemahan Struktural Komisi:
- Dominasi Internal: Keanggotaan yang didominasi oleh mantan pejabat Polri (purnawirawan) mengindikasikan terbatasnya pandangan kritis eksternal yang sangat dibutuhkan untuk reformasi menyeluruh.
- Konflik Kepentingan: Keberadaan pejabat aktif kabinet sebagai anggota, ditambah lagi dengan keikutsertaan Kapolri dalam struktur komisi, menimbulkan dilema etis dan logis. Bagaimana mungkin pihak yang menjadi objek reformasi ikut menentukan arah reformasi itu sendiri? Reformasi sejati memerlukan jarak institusional.
Komisi ini berisiko besar hanya menjadi forum koordinatif dan seremonial yang mengulang retorika lama, bukan agen independen pembaruan yang mampu menjawab krisis kepercayaan.
Jaminan Daya Ikat dan Payung Hukum
Meskipun terdapat Tim Transformasi Reformasi Internal Polri yang bekerja dari dalam, keberadaan Komisi eksternal harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Namun, persoalan krusial yang harus dijawab adalah: Apa status hukum Komisi ini? Apakah rekomendasinya mengikat atau hanya sebatas catatan normatif?
Agar Komisi ini efektif, perlu ada tiga aspek kritis yang harus diperhatikan:
- Status Kelembagaan: Komisi harus dilindungi oleh payung hukum yang kuat (idealnya Peraturan Presiden) agar tidak hanya bergantung pada political will sesaat.
- Kapasitas Rekomendasi: Hasil kerja harus berorientasi pada perubahan struktural, termasuk revisi UU Kepolisian, perbaikan regulasi kode etik, dan desain pengawasan eksternal yang independen.
- Daya Paksa: Rekomendasi harus memiliki mekanisme evaluasi kinerja transparan dan daya paksa yang menjamin implementasi oleh Polri.
Jika Komisi ini, yang sejatinya bersifat ad hoc, hanya diperlakukan sebagai simbol politik tanpa kewenangan yang mengikat, maka reformasi Polri akan kembali gagal menyentuh akar persoalan. Kita diingatkan oleh Francis Fukuyama bahwa perluasan peran negara tanpa peningkatan kapasitas institusi hanya akan melahirkan korupsi dan inefisiensi.
Oleh karena itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri harus diorkestrasi sebagai penugasan strategis langsung dari Presiden dengan guiding framework yang mengikat, menjadi penentu arah, bukan sekadar unit konsultatif. Jika tidak, optimisme publik akan segera tenggelam dalam skeptisisme institusional.